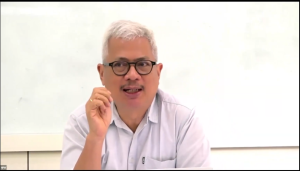Modul 4: Kepemimpinan dalam transformasi Kesehatan
“Pengembangan Kepemimpinan Klinik dalam sistem rujukan berbasis kompetensi (transformasi rujukan)”

Rabu, 7 Januari 2026 — Departemen Health Policy and Management Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menutup rangkaian Seri Seminar Reformasi Sistem Kesehatan melalui Sesi 11, yang merupakan bagian dari Modul 4: Kepemimpinan dalam Transformasi Kesehatan. Mengangkat tema “Pengembangan Kepemimpinan Klinik dalam Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi”, sesi ini diselenggarakan secara Hybrid di Auditorium Tahir FK-KMK UGM serta daring, dan menjadi ruang refleksi akhir untuk membahas peran kepemimpinan klinis dalam mendukung arah baru transformasi layanan kesehatan nasional.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang akademik dan praktik yang saling melengkapi, yakni Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada; Dr. dr. Ida Safitri Laksanawati, SpA(K), dosen Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM & RSUP Dr. Sardjito serta Dr. Cahya Dewi Satria, M.Kes, Sp.A, Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Kegiatan ini dirancang untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai peran kepemimpinan klinis dalam transformasi sistem rujukan nasional, dengan meninjau isu tersebut dari perspektif kebijakan, praktik klinis, dan manajemen rumah sakit, seiring pergeseran pendekatan dari struktur dan hierarki fasilitas menuju berbasis kompetensi layanan.
Pengantar: Pengembangan Kepemimpinan Klinik dalam Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi — Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Dalam sesi pengantar, Prof. dr. Laksono menempatkan kepemimpinan klinis sebagai isu strategis dalam transformasi sistem rujukan, bukan sekadar sebagai fungsi jabatan atau peran administratif. Ia menegaskan bahwa perubahan dalam sektor kesehatan saat ini berlangsung secara simultan baik pada level kebijakan, pembiayaan, maupun praktik klinik sehingga menuntut cara berpikir baru dalam memimpin layanan kesehatan. Prof. Laksono menjelaskan bahwa perubahan tersebut sebagian besar dipicu oleh dinamika eksternal, seperti reformasi regulasi, tuntutan mutu dan keselamatan pasien, serta perubahan desain sistem rujukan nasional. Dalam situasi ini, kepemimpinan klinis tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan mengelola unit layanan, melainkan sebagai kapasitas untuk memahami konteks perubahan, mengantisipasi dampaknya terhadap praktik klinik, dan mengambil keputusan berbasis pertimbangan klinis jangka panjang. Tanpa kemampuan tersebut, respons organisasi terhadap perubahan berisiko bersifat reaktif dan terfragmentasi.
Lebih lanjut, Prof. Laksono mengaitkan kepemimpinan klinis dengan pergeseran paradigma rujukan dari sistem berbasis kelas rumah sakit menuju rujukan berbasis kompetensi layanan. Pergeseran ini menuntut kejelasan mengenai siapa melakukan apa, pada tingkat kompetensi apa, dan dalam konteks layanan yang bagaimana. Dalam kerangka tersebut, klinisi khususnya dokter spesialis memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai aktor yang memengaruhi arah pengembangan layanan, mutu klinik, dan kesinambungan sistem rujukan. Oleh karena itu, kepemimpinan klinis menjadi prasyarat penting agar transformasi rujukan dapat diimplementasikan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan, alih-alih berhenti pada tataran kebijakan normatif.
Kepemimpinan Klinis (clinical leadership) Dalam Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi — Dr. dr. Ida Safitri Laksanawati, SpA(K)

Dalam paparan pertamanya, dr. Ida Safitri, dosen Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK-KMK UGM, memberikan perspektif kritis terhadap pemahaman yang masih memposisikan kepemimpinan klinis sebagai atribut jabatan struktural. Ia menjelaskan bahwa dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari, kepemimpinan sering kali dijalankan oleh klinisi yang tidak selalu berada pada posisi formal, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap cara kerja tim, kualitas pengambilan keputusan klinis, dan keselamatan pasien. dr. Ida menjelaskan bahwa kepemimpinan klinis tampak dalam praktik-praktik yang sering kali dianggap “biasa”, namun memiliki dampak besar, seperti kemampuan membangun komunikasi efektif antar profesi, mengoordinasikan kerja tim dalam situasi klinis yang kompleks, serta menjaga konsistensi mutu pelayanan di tengah tekanan beban kerja. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak selalu ditunjukkan melalui instruksi atau otoritas, melainkan melalui kemampuan memfasilitasi kerja kolektif dan memastikan setiap anggota tim memahami perannya dalam proses pelayanan.
Lebih lanjut, dr. Ida menekankan bahwa clinical leadership menuntut keseimbangan yang tidak sederhana antara keunggulan klinis dan kecerdasan emosional. Kompetensi medis yang tinggi, menurutnya, tidak secara otomatis menjadikan seseorang pemimpin klinis yang efektif. Seorang pemimpin klinis perlu mampu membangun kepercayaan, menjadi teladan dalam praktik profesional, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis sehingga anggota tim berani menyampaikan pendapat, keraguan, maupun pembelajaran dari kesalahan. Tanpa dimensi ini, upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sulit berjalan secara berkelanjutan. Berangkat dari pengalamannya dalam layanan kesehatan anak serta keterlibatan dalam berbagai kerja sama lintas institusi, dr. Ida merefleksikan bahwa kepemimpinan klinis sering tumbuh secara gradual dan kontekstual. Proses tersebut muncul melalui keterlibatan klinisi dalam penyusunan pedoman praktik klinis, pelaksanaan audit mutu, hingga kolaborasi dengan pemerintah dalam pengendalian penyakit. Dalam pengalaman tersebut, kepemimpinan tidak hadir sebagai peran yang ditetapkan sejak awal, melainkan berkembang seiring meningkatnya tanggung jawab terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien.
Pada bagian akhir paparannya, dr. Ida memperkenalkan pendekatan learning health system sebagai kerangka penting dalam pengembangan kepemimpinan klinis di layanan kesehatan. Ia memandang organisasi layanan kesehatan bukan sebagai struktur yang statis, melainkan sebagai sistem pembelajar yang terus berkembang melalui praktik sehari-hari. Dalam kerangka ini, upaya perbaikan tidak semata-mata dinilai dari pencapaian indikator akhir atau target kinerja, tetapi juga dari sejauh mana proses refleksi, evaluasi, dan pembelajaran kolektif benar-benar terjadi di dalam tim klinis. dr. Ida menjelaskan bahwa konsep learning loops membantu organisasi memahami kedalaman proses belajar tersebut. Single-loop learning berfokus pada perbaikan teknis dan prosedural, seperti penyesuaian alur layanan atau kepatuhan terhadap standar klinis. Double-loop learning mendorong tim untuk meninjau kembali asumsi dan cara berpikir yang mendasari praktik layanan, sementara triple-loop learning mengajak organisasi merefleksikan nilai, budaya kerja, dan tujuan yang membentuk pengambilan keputusan klinis. Melalui proses pembelajaran berlapis ini, kepemimpinan klinis tidak hanya diarahkan pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan pemimpin yang adaptif, reflektif, dan mampu memimpin perubahan secara berkelanjutan dalam konteks sistem kesehatan yang terus berkembang.
Penguatan Kepemimpinan Klinis dari Perspektif Manajemen SDM Rumah Sakit — Dr. Cahya Dewi Satria, M.Kes, Sp.A

Perspektif manajemen rumah sakit disampaikan oleh Dr. Cahya yang menyoroti kepemimpinan klinis dari sudut pandang pengelolaan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa kepemimpinan klinis tidak hanya berdampak pada proses pelayanan klinik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap iklim kerja organisasi, keberlanjutan tenaga kesehatan, dan pada akhirnya mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Menurut Dr. Cahya, kepemimpinan tidak dapat direduksi menjadi fungsi memberi arahan atau menetapkan target semata. Dalam konteks layanan kesehatan yang kompleks dan berisiko tinggi, pemimpin klinis justru berperan penting dalam menciptakan rasa aman secara psikologis (psychological safety) bagi staf. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan perlu merasa aman untuk menyampaikan pendapat, mengakui keterbatasan kompetensi, maupun mendiskusikan kesalahan dan kejadian tidak diinginkan tanpa rasa takut akan stigma atau sanksi. Tanpa kondisi tersebut, pembelajaran organisasi dan perbaikan mutu sulit berlangsung secara berkelanjutan.
Dr. Cahya juga mengaitkan kepemimpinan klinis dengan kapasitas emotional intelligence, terutama dalam mengelola tim di tengah tekanan kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan kinerja yang terus meningkat. Ia menekankan bahwa pemimpin klinis perlu memiliki kesadaran diri dan kepekaan sosial yang baik agar mampu memahami dinamika tim, merespons kelelahan kerja, serta menjaga hubungan profesional yang sehat. Dalam pandangannya, kepercayaan, komunikasi terbuka, dan komitmen bersama merupakan fondasi yang menentukan apakah sebuah tim klinik dapat bertahan dan berkembang dalam situasi perubahan. Dalam praktik kepemimpinan sehari-hari, dr. Cahya menekankan pendekatan connect then lead, yaitu membangun relasi dan pemahaman terlebih dahulu sebelum mendorong perubahan. Ia memandang bahwa perubahan yang dipaksakan tanpa relasi yang kuat justru berisiko menimbulkan resistensi. Konflik pun, menurutnya, tidak selalu harus dihindari, tetapi perlu dikelola secara profesional dan proporsional agar dapat menjadi sumber pembelajaran bersama, bukan pemicu disintegrasi tim. Pendekatan ini, ia tekankan, menjadi semakin relevan dalam konteks transformasi sistem rujukan dan penguatan peran klinisi sebagai pemimpin di lini layanan.
Sesi Pembahasan & Diskusi: Menjembatani Konsep dan Realitas Lapangan

Sesi diskusi berlangsung intens dan mencerminkan kegelisahan nyata para peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi layanan kesehatan, hingga mahasiswa. Diskusi bergerak dari tataran konseptual menuju persoalan implementasi, terutama terkait bagaimana kepemimpinan klinis dapat benar-benar berfungsi dalam konteks transformasi sistem rujukan berbasis kompetensi. Salah satu isu penting yang mengemuka adalah kesenjangan antara kepemimpinan klinis fungsional dan kepemimpinan struktural. Peserta menyoroti bahwa banyak klinisi memiliki pengaruh kuat dalam praktik pelayanan sehari-hari, namun tidak selalu berada pada posisi struktural yang memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan organisasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika pengembangan layanan, alokasi sumber daya, atau arah kebijakan internal rumah sakit ditentukan oleh struktur manajerial yang relatif jauh dari dinamika klinik. Diskusi menegaskan perlunya mekanisme yang mampu menjembatani dua ranah tersebut agar kepemimpinan klinis tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan strategis.
Dalam diskusi ini, Prof. dr. Badriul Hegar, Sp.A, Subsp. GH(K), Ph.D menyoroti aspek lain yang tak kalah krusial, yakni ketiadaan kerangka kerja yang sistematis untuk menilai dan mengembangkan kepemimpinan klinis. Ia mengemukakan bahwa selama ini penilaian kinerja klinisi masih sangat berfokus pada aspek teknis dan administratif, sementara kapasitas kepemimpinan yang justru berpengaruh besar terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien belum dinilai secara terstruktur. Tanpa kerangka penilaian yang jelas, kepemimpinan klinis berisiko dipahami sebagai kualitas personal semata, bukan sebagai kompetensi yang dapat dikembangkan, dievaluasi, dan diperkuat oleh sistem.
Isu lain yang mengemuka adalah tantangan memimpin generasi muda tenaga kesehatan di tengah perubahan karakteristik kerja dan ekspektasi profesional. Beberapa peserta berbagi pengalaman menghadapi tenaga kesehatan muda yang memiliki kapasitas teknis dan literasi digital yang tinggi, namun membawa nilai, gaya komunikasi, dan ekspektasi kerja yang berbeda dari generasi sebelumnya. Diskusi menekankan bahwa kondisi ini menuntut pendekatan kepemimpinan yang lebih dialogis dan adaptif, tanpa mengendurkan standar profesionalisme dan keselamatan pasien. Menanggapi berbagai isu tersebut, para narasumber sepakat bahwa tidak ada satu model tunggal kepemimpinan klinis yang dapat diterapkan secara universal. Kepemimpinan klinis perlu dipahami sebagai kapasitas yang berkembang sesuai konteks organisasi, jenis layanan, dan tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, diskusi menggarisbawahi benang merah yang konsisten, yakni pentingnya komunikasi yang efektif, refleksi diri, serta komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Diskusi juga menegaskan kembali bahwa transformasi sistem rujukan berbasis kompetensi hanya dapat berjalan secara konsisten apabila didukung oleh kepemimpinan klinis yang kuat, baik pada level individu klinisi
Penutup: Kepemimpinan Klinik sebagai Fondasi Transformasi
Sebagai penutup, Sesi 11 menegaskan bahwa kepemimpinan klinis merupakan fondasi penting dalam membangun sistem rujukan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan. Transformasi sistem kesehatan tidak dapat bergantung pada perubahan regulasi, struktur organisasi, atau desain sistem semata, tetapi membutuhkan kehadiran pemimpin klinis yang mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pelayanan sehari-hari, sekaligus menjembatani kepentingan klinik, manajerial, dan sistem kesehatan secara lebih luas. Diskusi dalam sesi ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan klinis memiliki kontribusi yang relevan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan peran klinisi sebagai pemimpin layanan mendukung SDG 3 (Good Health and Well-being) melalui peningkatan mutu dan keselamatan pasien; berkontribusi pada SDG 4 (Quality Education) melalui pengembangan kapasitas kepemimpinan dan pembelajaran berkelanjutan di lingkungan layanan kesehatan; serta memperkuat SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi lintas profesi dan lintas institusi dalam sistem rujukan dan pengembangan layanan. Sesi ini sekaligus menutup rangkaian kuliah terbuka dengan satu refleksi kunci: keberhasilan transformasi sistem kesehatan Indonesia pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan klinis yang dibangun hari ini—kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga reflektif, inklusif, dan mampu menumbuhkan budaya belajar dalam jangka panjang.
Reporter:
- Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb., MHPM
- Erti Nur Sagenah, S.Kep., Ners., M.N.Sc
- Aninditya Ratnaningtyas, S.Gz., M.Sc
- dr. Fadhilah Khairuna Larasati